Nestapa Penulis di Tengah Lesunya Industri Buku: Antara Rendahnya Minat Baca, Gempuran Teknologi, dan Harapan untuk Bangkit
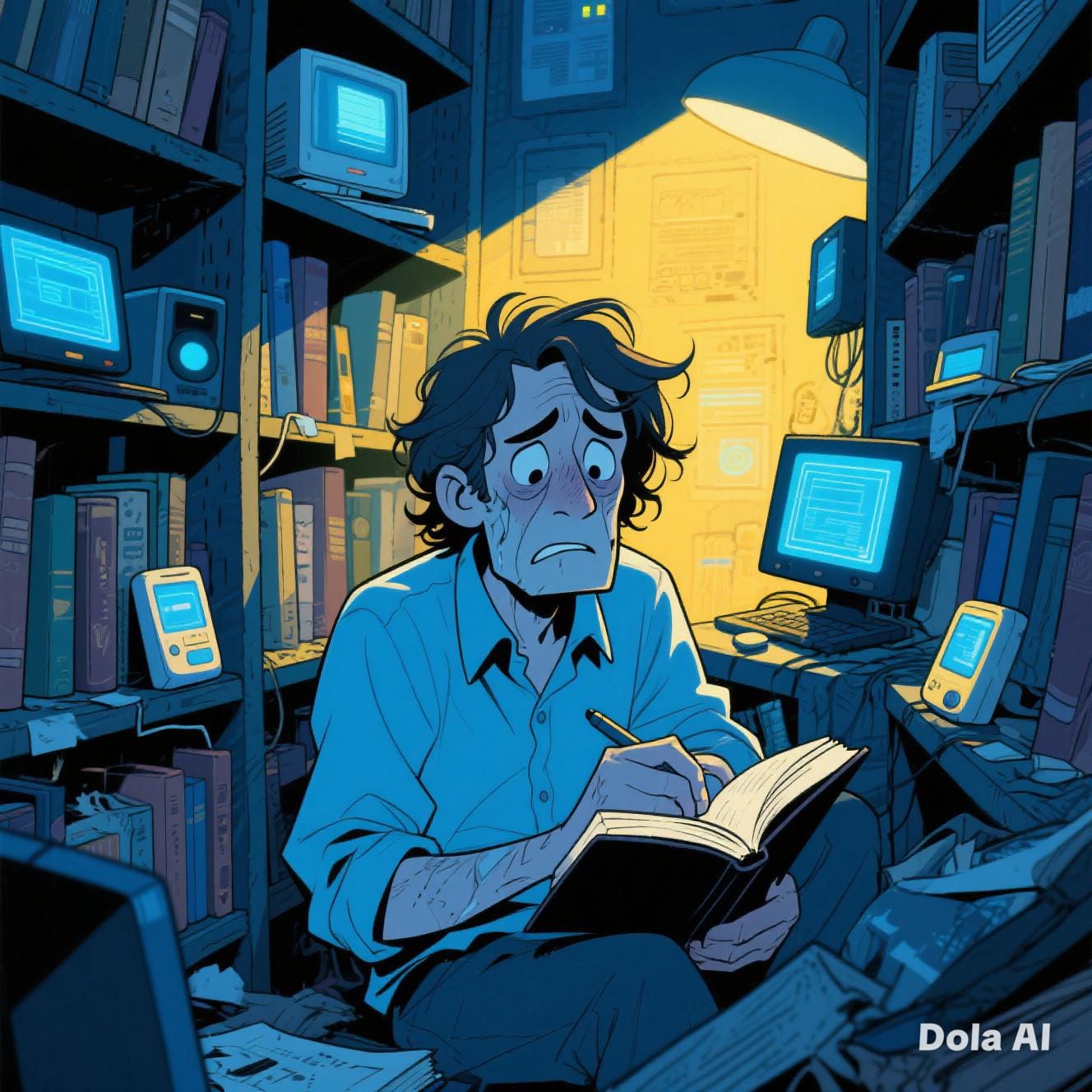
Nestapa Penulis di Tengah Lesunya
Industri Buku: Antara Rendahnya Minat Baca, Gempuran Teknologi, dan Harapan
untuk Bangkit
Oleh : Desak Putu Suastini
Di tengah pesatnya kemajuan teknologi
informasi, industri buku justru menghadapi keterpurukan yang kian dalam. Buku,
yang selama ini menjadi simbol peradaban dan sarana utama penyebaran ilmu
pengetahuan, kini seolah tergeser oleh konten instan dan hiburan digital. Tidak
sedikit penerbit kecil yang gulung tikar, toko buku independen tutup, dan para
penulis kehilangan ruang serta penghasilan yang layak. Dunia perbukuan, yang
dahulu penuh gairah intelektual, kini terpinggirkan di tengah dominasi
algoritma media sosial dan pola konsumsi informasi yang serba cepat. Sementara
itu, penulis—yang semestinya menjadi pilar kebudayaan dan pengetahuan—terjebak
dalam ruang sunyi, tanpa jaminan hidup layak maupun apresiasi yang setimpal.
Salah satu penyebab utama keterpurukan
ini adalah rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari
UNESCO yang banyak dikutip, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen.
Artinya, dari seribu orang Indonesia, hanya satu orang yang benar-benar
memiliki kebiasaan membaca. Survei yang dilakukan Central Connecticut State
University pada tahun 2016 menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 61
negara dalam hal literasi. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah
penduduk besar dan akses informasi semakin terbuka, budaya membaca belum
menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Indeks
Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) dari Perpustakaan Nasional RI tahun 2022
juga hanya mencatat skor 59,52 dari 100—masih dalam kategori sedang. Sementara
itu, indeks literasi digital Indonesia tahun 2022 dari Kominfo mencatat skor
3,54 dari skala 1 hingga 5, yang juga menandakan literasi digital belum cukup
matang, khususnya dalam aspek berpikir kritis dan konsumsi informasi yang berkualitas.
Rendahnya minat baca ini turut
diperparah oleh hadirnya teknologi informasi yang seharusnya menjadi alat
pendukung literasi, namun justru melahirkan budaya konsumsi informasi yang
dangkal dan cepat. Masyarakat kini lebih tertarik pada konten-konten video
pendek, meme, dan berita viral ketimbang membaca buku. Algoritma media sosial
didesain untuk menonjolkan konten yang menghibur, mudah dipahami dalam hitungan
detik, dan mengundang interaksi cepat, bukan konten-konten mendalam yang
membutuhkan konsentrasi dan perenungan. Akibatnya, ruang bagi buku dan penulis
menjadi semakin sempit, karena perhatian publik telah direbut oleh layar-layar
berpendar yang menawarkan hiburan instan dan sensasi sesaat.
Dampaknya sangat terasa bagi para
penulis. Bagi mereka, menulis bukan hanya pekerjaan, tetapi juga jalan hidup,
panggilan intelektual, dan bentuk kontribusi terhadap masyarakat. Namun, dalam
kondisi saat ini, menulis buku bukanlah jaminan kesejahteraan. Royalti yang
diterima penulis di Indonesia umumnya berkisar antara 8 hingga 12 persen dari
harga jual buku. Artinya, dari sebuah buku seharga Rp100.000, penulis hanya
menerima sekitar Rp8.000 hingga Rp12.000 per eksemplar. Jika buku itu hanya
terjual 1.000 eksemplar—angka yang bahkan sudah dianggap bagus oleh standar
lokal—maka total royalti yang diterima penulis hanya Rp8 juta hingga Rp12 juta,
jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan waktu, tenaga, dan biaya
riset yang dibutuhkan untuk menulis buku tersebut.
Kondisi ini membuat banyak penulis
harus mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup. Tidak sedikit dari mereka
yang memilih menjadi guru, penerjemah, editor, bahkan beralih menjadi konten
kreator karena lebih menjanjikan dari segi pendapatan. Pilihan ini seringkali
diambil dengan berat hati, karena harus meninggalkan idealisme dan gairah dalam
menulis. Sementara itu, penerbit independen kesulitan bertahan karena biaya
produksi yang tinggi, fluktuasi harga kertas, serta menurunnya daya beli
masyarakat. Toko buku fisik juga terdesak oleh platform e-commerce yang menjual
buku dengan diskon besar, namun minim kurasi dan promosi karya lokal yang
bermutu.
Namun demikian, bukan berarti tidak
ada upaya yang telah dilakukan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Perpustakaan Nasional telah
meluncurkan berbagai program literasi seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN),
penyediaan perpustakaan digital seperti iPusnas, serta kerja sama dengan
komunitas literasi di berbagai daerah. Beberapa komunitas seperti Forum Lingkar
Pena, Taman Baca Masyarakat, hingga gerakan book-sharing berbasis media sosial
juga menunjukkan semangat akar rumput dalam membumikan literasi. Namun upaya
ini belum cukup jika tidak dibarengi dengan perubahan budaya membaca di
lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas.
Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan
pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pertama, literasi harus ditanamkan
sejak usia dini. Pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu diarahkan untuk
menumbuhkan kegemaran membaca, bukan sekadar mengenalkan huruf dan angka. Orang
tua perlu dilibatkan melalui program “membacakan buku” di rumah agar anak-anak
tumbuh dalam lingkungan yang akrab dengan bacaan. Pemerintah daerah juga harus
memastikan setiap sekolah memiliki perpustakaan yang layak, lengkap dengan
buku-buku terbaru dan pustakawan yang kompeten. Tidak kalah penting, guru harus
diberi pelatihan untuk menjadikan kegiatan membaca sebagai pengalaman yang
menyenangkan, bukan tugas yang membosankan.
Kedua, perlu perbaikan akses terhadap
buku. Masih banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki toko buku, dan
distribusi buku baru cenderung terpusat di kota-kota besar. Pemerintah dapat
memberikan subsidi ongkos kirim untuk buku ke daerah terpencil, serta
mengembangkan perpustakaan digital yang dapat diakses gratis. E-book dengan
harga terjangkau, atau bahkan gratis untuk pelajar, bisa menjadi solusi agar
generasi muda tetap bisa membaca tanpa terhalang biaya. Platform digital
seperti iPusnas, Storial, atau Google Play Books bisa dimanfaatkan untuk
memperluas jangkauan distribusi karya lokal.
Ketiga, perlu adanya insentif konkret
bagi penulis dan penerbit. Pemerintah dapat memberikan subsidi cetak,
pembebasan pajak royalti, hingga program bantuan riset bagi penulis yang
menulis buku berbasis data dan kajian serius. Kompetisi menulis dengan hadiah
yang layak dan dukungan publikasi juga bisa menjadi cara untuk memunculkan
penulis-penulis muda berbakat. Selain itu, karya penulis lokal perlu mendapat
tempat dalam kurikulum pendidikan agar pelajar dapat mengenal dan mengapresiasi
hasil karya anak bangsa sejak dini.
Keempat, teknologi seharusnya
dijadikan sebagai alat bantu literasi, bukan saingan. Pemerintah, pelaku
industri kreatif, dan komunitas teknologi bisa berkolaborasi membuat aplikasi
membaca yang interaktif, gamifikasi literasi, serta konten edukatif di platform
digital populer. Festival literasi daring, podcast buku, kanal YouTube yang
membahas resensi buku, dan ruang diskusi daring adalah contoh penggunaan
teknologi untuk memperkuat budaya membaca, bukan sebaliknya.
Kelima, gerakan literasi harus menjadi
bagian dari gaya hidup masyarakat. Figur publik dan influencer dapat dilibatkan
untuk mengampanyekan pentingnya membaca. Kampanye nasional seperti “Satu Hari
Satu Buku”, “BookTube Indonesia”, atau gerakan membaca di transportasi umum
bisa menjadi cara untuk menormalisasi budaya membaca di ruang publik. Media
massa juga dapat mengangkat profil penulis, ulasan buku, serta diskusi literasi
sebagai bagian dari program reguler mereka.
Keenam, sistem pendidikan perlu
direformasi agar membaca dan menulis tidak sekadar menjadi formalitas akademik,
tetapi menjadi bagian dari pembentukan karakter dan daya pikir. Kurikulum harus
memberi ruang untuk apresiasi sastra, refleksi terhadap bacaan, serta
pengembangan kemampuan menulis kreatif. Pelajar tidak hanya diuji pada
pengetahuan hafalan, tetapi juga kemampuan menafsirkan, menganalisis, dan
menulis argumen berbasis bacaan.
Pada akhirnya, menyelamatkan industri
buku bukan hanya soal menyelamatkan penerbit, toko buku, atau penulis. Ini
adalah tentang menyelamatkan fondasi intelektual bangsa. Buku masih memiliki
kekuatan untuk mengubah cara pandang, memperluas wawasan, dan membentuk manusia
yang berpikir kritis dan berempati. Jika kita terus membiarkan budaya membaca
memudar, maka yang kita pertaruhkan bukan hanya nasib industri buku, tetapi
arah masa depan bangsa.
Masyarakat yang tidak membaca adalah
masyarakat yang mudah terombang-ambing oleh hoaks, manipulasi informasi, dan
kehilangan kemampuan membedakan kebenaran dari sensasi. Sebaliknya, bangsa yang
membaca adalah bangsa yang mampu menulis sejarahnya sendiri, merancang masa
depannya, dan menavigasi tantangan zaman dengan kecerdasan dan kematangan.
Untuk itu, mari kita hidupkan kembali semangat literasi, bukan hanya untuk hari
ini, tetapi untuk generasi yang akan datang.
