Thrifting Tak Lagi Sekadar Gaya: Saat Tren Bekas Menjadi Masalah Serius
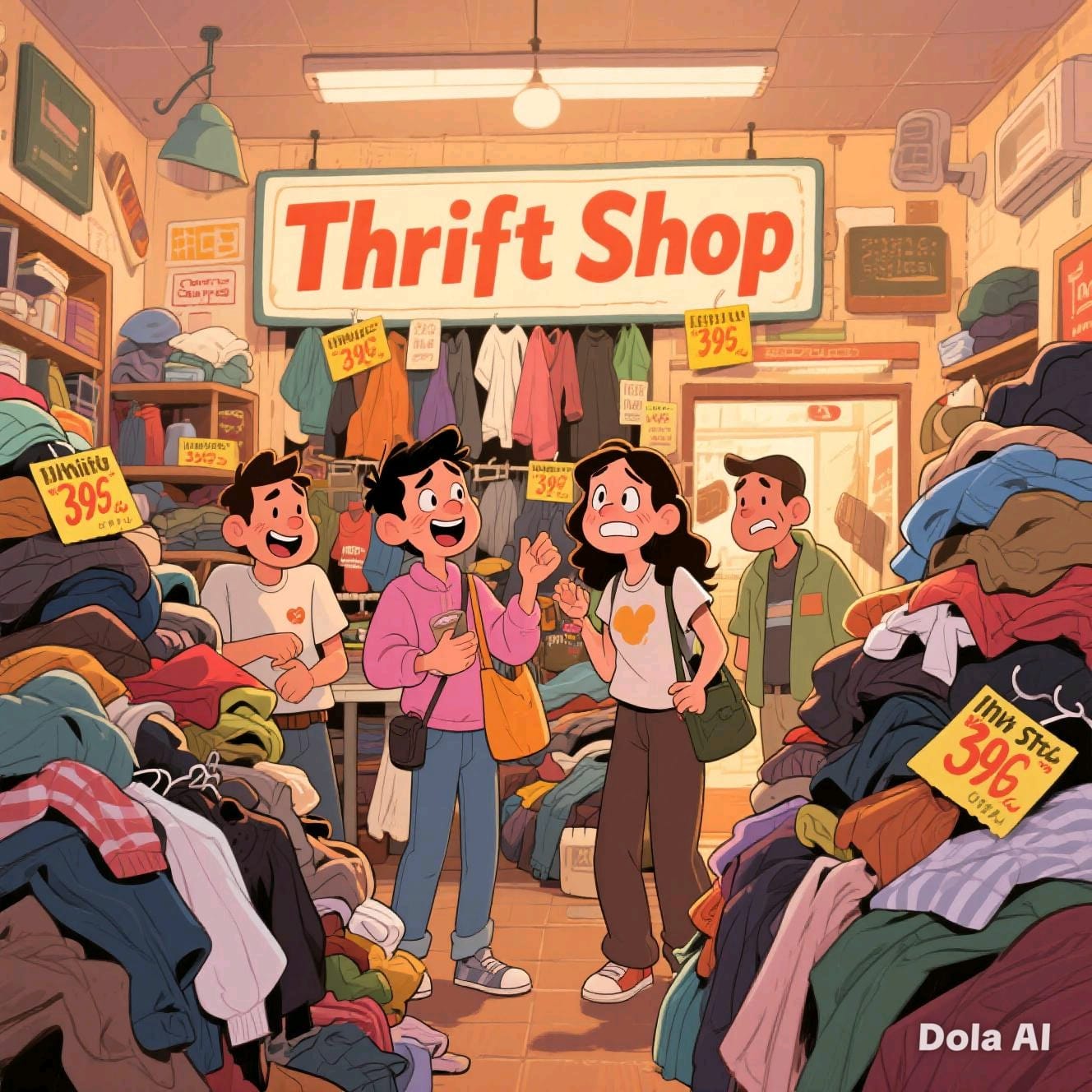
Thrifting Tak Lagi Sekadar Gaya: Saat Tren Bekas Menjadi Masalah Serius
Fenomena thrifting atau pembelian baju bekas yang dahulu dipandang sebagai bentuk kesederhanaan dan kepedulian terhadap lingkungan kini telah menjelma menjadi tren gaya hidup yang kompleks. Dulu, thrifting dianggap sebagai upaya cerdas untuk mengurangi limbah mode dan memperpanjang umur pakaian yang masih layak pakai. Kini, di tengah derasnya arus globalisasi dan budaya digital, thrifting justru menjadi simbol gaya hidup baru—perpaduan antara kesadaran sosial, pencitraan diri, dan bahkan gengsi. Ironisnya, di balik gemerlap tren ini tersimpan persoalan serius yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan budaya konsumsi masyarakat Indonesia.
Tren thrifting berkembang pesat beriringan dengan perubahan pola belanja dan gaya hidup generasi muda, terutama Gen Z dan milenial. Di media sosial, muncul berbagai konten “thrift haul” dan “thrift flip” yang menampilkan pakaian bekas bermerek luar negeri seperti Zara, Levi’s, H&M, hingga Gucci, yang dibeli dengan harga murah lalu dipadukan menjadi tampilan modis dan estetik. Aktivitas ini dinilai keren, berjiwa muda, dan berkesadaran lingkungan. Namun di sisi lain, ada pergeseran makna yang cukup tajam—dari kesadaran lingkungan menjadi ajang pencitraan gaya hidup. Banyak orang membeli pakaian bekas bukan lagi karena kebutuhan, melainkan karena ingin tampil “branded” dengan cara yang lebih terjangkau.
Fenomena ini sekaligus membuka tabir tentang kecenderungan masyarakat Indonesia yang masih mengagungkan barang impor. Seolah-olah, produk luar negeri memiliki nilai lebih tinggi, prestise lebih besar, dan kualitas lebih unggul dibandingkan produk dalam negeri. Dalam konteks thrifting, banyak pembeli memburu pakaian bekas bermerek dari luar negeri tanpa mempedulikan asal-usul dan kebersihannya, karena label asing di pakaian dianggap mampu menaikkan status sosial dan rasa percaya diri. Pola pikir semacam ini menunjukkan bahwa kolonialisme kultural masih melekat kuat dalam cara pandang masyarakat kita—bahwa sesuatu yang berasal dari luar negeri selalu lebih “berharga” daripada buatan bangsa sendiri.
Padahal, sebagian besar pakaian thrifting impor yang beredar di pasaran bukanlah barang bermerek premium, melainkan sisa donasi massal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, atau Jepang. Barang-barang ini dikirim ke negara berkembang sebagai limbah tekstil yang kemudian diseleksi dan dijual kembali. Tidak jarang pakaian tersebut sudah rusak, kotor, atau bahkan mengandung jamur dan residu bahan kimia. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 akhirnya menegaskan larangan impor pakaian bekas karena praktik tersebut telah merugikan industri tekstil nasional dan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.
Dari sisi ekonomi, maraknya thrifting impor telah menimbulkan tekanan besar terhadap pelaku industri tekstil dan usaha konveksi dalam negeri. Produk pakaian lokal yang dibuat dengan biaya produksi dan tenaga kerja lebih tinggi harus bersaing dengan pakaian bekas impor yang dijual jauh lebih murah. Hal ini menyebabkan turunnya daya saing produk nasional, berkurangnya permintaan pasar, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja di sektor garmen. Industri pakaian dalam negeri, yang sebelumnya menjadi salah satu penopang ekspor nonmigas, kini menghadapi tantangan berat karena konsumen cenderung beralih ke produk impor, termasuk pakaian bekas.
Dari sisi sosial, thrifting juga menimbulkan paradoks baru. Dulu, pasar pakaian bekas dikenal sebagai tempat alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pakaian layak dengan harga terjangkau. Kini, pasar itu telah “diambil alih” oleh kalangan menengah ke atas dan para reseller yang membeli secara besar-besaran untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, pakaian bekas yang semestinya menjadi solusi kebutuhan rakyat kecil berubah menjadi komoditas tren yang meminggirkan kelompok ekonomi bawah. Fenomena ini dikenal sebagai thrift gentrification—ketika praktik berhemat dan keberlanjutan justru menjadi bagian dari konsumsi bergaya dan eksklusif.
Lebih jauh, thrifting juga menyentuh dimensi psikologis masyarakat modern. Di era digital yang sarat dengan pencitraan diri, banyak orang merasa perlu menampilkan gaya hidup tertentu untuk memperoleh pengakuan sosial. Pakaian bermerek, meski bekas sekalipun, menjadi simbol status baru yang dianggap mewakili kecerdasan, selera, dan kelas sosial. Inilah yang disebut sosiolog Jean Baudrillard sebagai “masyarakat konsumsi tanda”, di mana nilai sebuah barang tidak lagi diukur dari fungsi atau kualitasnya, tetapi dari citra yang melekat padanya. Dengan kata lain, pakaian bekas bermerek bukan lagi sekadar benda, melainkan simbol gaya hidup yang dikejar banyak orang.
Sayangnya, obsesi terhadap citra dan merek ini kerap menutupi esensi keberlanjutan yang menjadi dasar gerakan thrifting itu sendiri. Tujuan awal thrifting adalah memperpanjang umur pakai pakaian dan mengurangi produksi baru yang boros sumber daya alam. Namun, ketika thrifting berubah menjadi ajang belanja massal dan konsumsi impulsif, nilai keberlanjutannya pun hilang. Banyak orang membeli pakaian bekas dalam jumlah banyak hanya untuk konten media sosial, lalu menumpuknya di lemari atau bahkan membuangnya kembali. Siklus ini, pada akhirnya, tetap menciptakan limbah baru dan memperparah masalah lingkungan yang semula ingin diatasi.
Pemerintah tidak serta-merta menentang thrifting secara total. Yang menjadi masalah utama adalah masuknya pakaian bekas impor ilegal dalam jumlah besar tanpa izin resmi dan tanpa pengawasan kebersihan. Larangan impor bukan berarti menolak konsep thrifting, melainkan melindungi industri dalam negeri dan kesehatan publik. Praktik thrifting lokal sejatinya tetap dapat dijalankan dengan cara yang bijak: membeli pakaian bekas dari sumber lokal, mendaur ulang atau memperbaiki pakaian lama, dan mengubahnya menjadi produk baru yang kreatif dan bernilai tambah. Inilah esensi sustainable fashion yang sebenarnya—bukan sekadar bergaya hemat, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat.
Masalah yang lebih dalam justru terletak pada pola pikir masyarakat terhadap gaya hidup dan status sosial. Kecenderungan untuk selalu menyukai barang impor menunjukkan adanya ketergantungan psikologis terhadap citra global, sekaligus lemahnya kebanggaan terhadap produk lokal. Padahal, banyak produk pakaian Indonesia kini memiliki kualitas tinggi, desain kreatif, dan nilai budaya yang kuat. Namun karena tidak berlabel asing, sering kali produk lokal dianggap kurang bergengsi. Pola pikir inilah yang perlu diubah melalui edukasi dan literasi gaya hidup, agar masyarakat tidak terjebak pada ilusi merek dan mulai menilai sesuatu dari nilai fungsional dan kebermanfaatannya.
Di era modern yang serba cepat, masyarakat seolah berlomba menampilkan diri sebagai “modern dan sadar lingkungan”, tetapi sering kali lupa bahwa keberlanjutan sejati dimulai dari kesederhanaan dan tanggung jawab pribadi. Berpakaian sederhana dengan produk lokal bukanlah tanda keterbelakangan, melainkan bentuk kemandirian dan kepedulian sosial. Sementara itu, kebiasaan membeli barang bekas impor demi citra “branded” justru memperlihatkan paradoks antara kesadaran dan keinginan.
Akhirnya, thrifting perlu dipahami ulang: bukan tentang gengsi, bukan tentang merek, dan bukan tentang mengikuti tren. Thrifting seharusnya menjadi wujud kesadaran ekologis, bentuk solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap nilai-nilai produksi yang beretika. Masyarakat perlu belajar membedakan antara thrifting yang bijak dan thrifting yang konsumtif. Bijak berarti membeli seperlunya, mendukung usaha lokal, dan menjaga kebersihan serta keberlanjutan; sementara konsumtif berarti membeli berlebihan demi tren dan citra diri semu.
Jika generasi muda mampu memahami perbedaan itu, maka thrifting bisa kembali ke makna aslinya: gerakan sederhana untuk menyelamatkan bumi dan memperkuat ekonomi lokal. Sebaliknya, jika thrifting terus dibiarkan sebagai bentuk pencitraan dan ketergantungan terhadap barang impor, maka yang tersisa hanyalah tumpukan pakaian bekas—bukan kesadaran baru, melainkan masalah lama dalam wajah yang lebih modis. Karena pada akhirnya, nilai seseorang tidak ditentukan oleh merek di bajunya, tetapi oleh pikiran, perilaku, dan kontribusi nyata yang ia berikan kepada sesama dan lingkungannya.
#banggamelayanibangsa
#BerAKHLAK
#bulelengPATEN
